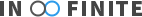“Nah, ini dia, pala walor!” seru Pongky van der Broeke seraya menunjuk benda hitam kecil yang terserak di antara rerumputan di perkebunan pala miliknya yang luas—lebih dari 12 hektare—di Banda Besar, Maluku Tengah. Saya memungut benda itu: biji pala walor yang bulat utuh tanpa fuli, daging buah, dan kulitnya.
“Pala walor lebih hitam daripada pala yang dipanen oleh para petani,” kata Pongky menambahkan. Cerita tentang pala walor pun bergulir. Sejak 1989, Pongky terlibat total dalam mengelola perkebunan dan produksi pala (juga kenari) yang merupakan warisan dari leluhurnya, perkenier (perquenier) keturunan Belanda.
Inilah hal yang saya suka dari suatu perjalanan: pasti ada pengetahuan dan pengalaman baru yang seru, juga menarik. Dan perjalanan ke Kepulauan Banda, beberapa waktu lalu, bersama beberapa rekan, ini sungguh membukakan mata saya tentang keberadaan pala walor, yang nyaris tidak pernah saya dengar sebelumnya.
Sebetulnya, saya sudah lebih dahulu mendengar cerita tentang pala walor dari Rusdi Takartutun, pemuda dari Desa Selamun, Banda Besar, yang saya temui di Banda Neira, saat berlangsung suatu acara di salah satu bangunan kuno peninggalan kolonial Belanda. Tetapi baru di perkebunan milik Pongky itulah saya melihat wujudnya.
Saya pun mencari tahu lebih banyak tentang pala, rempah asli Kepulauan Maluku. Dalam sebuah kajian yang disusun oleh Marfin Lawalata, Stephen F.W. Thenu, Misco Tamaela dari Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, disebutkan bahwa pala Banda (Myristica fragrans Houtt) adalah jenis pala berkualitas terbaik di dunia.

Mengutip sebuah sumber, Marfin Lawalata dkk memaparkan, bahwa tanaman yang merupakan spesies genetik dari genus Myristicaceae yang tersebar luas di wilayah Kepulauan Banda ini yang telah ada sebelum awal kedatangan bangsa Portugis di Maluku pada 1271 sampai 1295, yang dibawa oleh para pedagang Arab.
“Sejak abad ke-16,” sebagaimana diulas oleh Marfin Lawalata dkk dalam kajiannya, “Banda sudah dikenal sebagai penghasil pala berkualitas dunia sehingga tidak mengherankan jika beberapa bangsa asing berlomba untuk menguasai daerah sumber penghasil rempah berkualitas dunia ini.” Salah satunya, bangsa Belanda.
Adapun fakta yang disampaikan oleh Marfin Lawalata dkk, bahwa di wilayah Kepulauan Banda terdapat bekas perkebunan kekuasaan Belanda (perk) sebagai hasil monopoli seluruh tanaman pala milik rakyat dan kemudian menjadikannya sebagai perkebunan pala milik Kolonial Belanda (V.O.C) hingga berunjung konflik pada waktu itu.
Saat ini, menurut hasil riset Marfin Lawalata dkk, perkebunan pala yang tersebar di Kepulauan Banda masing-masing telah dibudidayakan dari generasi ke generasi dengan pola perkebunan rakyat dan sebagian di bawah pengelola pemerintah daerah (pemda) setelah seluruh aset milik kolonial Belanda dinasionalisasikan dan menjadi aset pemda.

Literatur tentang pala memang cukup banyak. Tetapi saya belum menemukan yang spesifik tentang pala walor. Marfin Lawalata dkk sebatas menuliskan, “Biji pala hasil kotoran burung yang oleh masyarakat lokal disebut sebagai burung walor/pombu (Bahasa Indonesia) yang disebutkan sebagai biji pala kualitas super yang dihargai tinggi di pasaran.”
Begitu pun artikel berjudul Banda, Potret Ekowisata di Bumi Maluku yang ditulis oleh Revalda AJB Salakory dan dimuat di www.kompasiana.com (April 2016), hanya menyebutkan, “Wisatawan juga dapat menikmati suara dan kecantikan fauna khas yang hidup di hutan tersebut, yaitu burung walor, nuri dan kakatua yang dilindungi habitatnya.”
Ada pula cerita pendek berjudul Pulau Banda dan Diana karangan Almin Patta yang dimuat di bukuprogresif.com (Maret 2019), yang menggambarkan, “Kawanan burung walor terbang rendah membelah langit Banda. …bertebaran ke segala penjuru mata angin berebutan tempat di kuncup pohon pala hendak memakan buahnya yang segar merekah.”
Pada akhirnya cerita autentik tentang pala walor saya dapatkan dari native speaker: Rusdi dan Pongky. Keduanya mengakui, sejak kecil sudah senang berburu pala walor. Sebagian besar anak di Kepulauan Banda melakukan itu! Jika sanggup mengumpulkan dalam jumlah banyak, maka bayaran yang didapat pun tidak sedikit.

Lazimnya, buah pala dipanen atau dipetik oleh para petani dengan menggunakan alat tradisional yang disebut takiri dan gai-gai yang terbuat dari bambu. Namun tidak demikian halnya pala walor. Lantaran berserakan di tanah atau rerumputan, maka tinggal dipulung atau dipungut begitu saja. Tindakan ini dianggap legal.
“Jadi,” Rusdi menjelaskan, “buah pala yang masih ada di pohon adalah milik perkenier atau petani. Tetapi biji pala walor yang sudah jatuh dan berserak di tanah atau rerumputan adalah milik umum. Boleh-boleh saja diambil oleh siapa pun.” Lalu, bagaimana biji pala bisa jatuh ke tanah? Siapa gerangan yang menjatuhkan?
Biang keladinya tak lain: si burung walor! “Jadi,” sekali lagi Rusdi menerangkan, “burung walor memakan kulit dan daging buah pala yang sudah matang dan merekah, termasuk fuli atau selaput merah yang melapisi biji pala. Lalu, burung walor membuang kotoran berupa biji pala utuh yang jatuh ke tanah dan oleh orang sini disebut bobot.”
“Oh, mirip kopi luwak, ya,” saya menyahut. Untuk diketahui, luwak memakan buah kopi dan membuang kotoran berupa biji kopi yang berkualitas dan bernilai tinggi. Namun Rusdi tidak sependapat. Menurutnya, “Pala walor memang berkualitas tinggi, tetapi harganya kurang lebih sama dengan pala yang dipanen oleh para petani.”
Hal ini dibenarkan oleh Pongky, “Dahulu, pala walor memang dihargai mahal, tetapi sekarang tidak lagi. Kualitas pala walor memang bagus, namun entah kenapa harga di pasaran tidak ada perbedaan, tidak lebih mahal. Maka saat dijual pun tidak dipisah antara pala walor hasil pulungan dan pala hasil panen. Ya, dicampur.”
Jumlah pala walor hasil pulungan dari perkebunannya, menurut Pongky, hanya sekitar lima persen saja. Selebihnya, pala hasil panen dengan cara regular—menggunakan takiri dan gai-gai—oleh para petani. Selain diolah sebagai bahan baku obat dan kosmetik, pala juga dijadikan produk olahan: selai, sirup, jus, manisan, minyak, permen, dodol.

Saat menyinggahi tempat tinggal Rusdi di Desa Selamun, Banda Besar, saya bertemu beberapa anak yang baru saja memulung pala walor, sepulang sekolah. Tas pinggang atau tas ransel mereka penuh berisi pala walor. “Berapa harga jualnya?” saya bertanya. “Tiap sepuluh butir bobot dihargai tiga puluh ribu,” kata salah seorang bocah.
Spontan saya menghitung: jika dalam sehari seorang anak mampu memulung 100 butir pala walor alias bobot, maka ia bisa menerima Rp300.000! Wow, luar biasa! Menurut Rusdi, inilah berkah warga yang meskipun tidak memiliki kebun pala, tetap bisa mendapatkan keuntungan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Saya pun merasa senang ketika akhirnya bisa “bertemu” kawanan burung walor yang beterbangan ke sana kemari di pucuk pohon pala yang menjulang tinggi, saat berkeliling Banda Besar bersama seorang rekan, ditemani Rusdi dan sahabatnya, Dion Robusta. Sekilas, walor mirip merpati dengan bulu kepala putih dan bulu badan hitam.
Saya berharap ke depannya akan tersedia data yang lebih detail tentang pala walor alias bobot. Mengingat rempah yang satu ini punya potensi sebagai pesaing kopi luwak, dengan adanya kesamaan: si hewan memakan buah dan mengeluarkan kotoran berupa biji yang secara alami matang sempurna sehingga berkualitas tinggi.
Terlepas dari minimnya data, saya salut dengan cara warga Banda merekonstruksi dan merevitalisai Jalur Rempah dengan tetap mempertahankan perkebunan pala. Kegiatan memulung pala walor terus diestafet dari generasi ke generasi. Sebentuk keberlanjutan yang bakal membuat si hitam manise kelak menjadi primadona, pesaing kopi luwak yang mendunia.
Penulis: Vega Probo, Editor