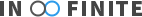Saya “mengenal” dia sejak lama. Pertama kali melalui video pendek berbahasa Belanda di YouTube, pada 2012. Berikutnya, lima tahun kemudian, melalui film dokumenter Banda, The Dark Forgotten Trail karya Jay Subiyakto. Pada tahun yang sama—2017, saya menyinggahi Banda, namun tak sempat bersua dengan dia.
Akhirnya, empat tahun kemudian, saya bertemu dengan dia: sang perkenier terakhir, Pongky van den Broeke! Pria ramah berusia 65 tahun ini adalah keturunan—generasi ke-13—dari Paulus van den Broeke, perkenier alias pemilik/pengelola perken (perkebunan pala dan kenari) terbesar di Kepulauan Banda, pada abad ke-17.
Sedikit mengilas balik, ratusan tahun silam, pala dari Banda menjadi primadona dunia, bahkan harganya melampaui harga emas. Nama kepulauan di Maluku Tengah ini pun menjadi “trending topic” sehingga bangsa Eropa berlomba-lomba untuk menguasai perdagangan pala asli Banda yang memang berkualitas terbaik.
Demi pala, Belanda dan Inggris berperang. Lalu, pada 1667, keduanya menyepakati Traktat Breda yang antara lain menetapkan Inggris harus mengakhiri kekuasaan di Pulau Run, Kepulauan Banda, dan menyerahkan kepada Belanda. Di sisi lain, koloni Belanda, Nieuw Amsterdam di Amerika Serikat (kini Manhattan, New York) diserahkan ke Inggris.
Semula hanya penduduk sipil Belanda atau pegawai Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang menjadi perkenier, sedangkan warga sipil Banda tidak diperkenankan. Singkat cerita, pasca Kemerdekaan RI, keluarga van den Broeke menjadi perkenier terakhir yang mengelola perkebunan pala seluas 12,5 hektare.

Padahal sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam buku The Banda Journal karya Fatris M.F. dan M. Fadli, keluarga van den Broeke memiliki lahan seluas 140 hektare. Sejak 1999, Mas Pongky—begitu ia biasa disapa lantaran pernah menetap lama di Surabaya, Jawa Timur—menerima tongkat estafet sebagai penerus perkenier.
Saya tentu saja senang bisa bertemu dengan Mas Pongky di Desa Walang, Banda Besar. Tanpa membuang waktu, saya segera mengambil alat gambar dan membuat sketsa beliau serta gerbang rumahnya yang bersisian dengan pantai. Saya juga menuliskan sekelumit kisah tentang pala dan sejarah keluarga van den Broeke.
Mas Pongky menuturkan, suatu hari pada 1990, ia mendapat pesan telegram dari sang ayah, Benny Willem van den Broeke, yang memintanya pulang kampung untuk mengurus perkebunan. Mas Pongky pun melepas pekerjaannya sebagai mekanik di Jakarta untuk menggantikan tugas Benny Willem sebagai perkenier.
“Tidak satu pun anak dari Benny Wiliem mau melanjutkan pengelolaan perkebunan pala,” curhat Mas Pongky, yang mengaku terakhir kali pulang kampung, pada 1988, untuk menengok keluarga pasca bencana erupsi gunung api. Mas Pongky tak memungkiri, telegram dari sang ayah membuat hatinya benar-benar tersentuh.
Ia pun kembali ke Banda Besar dan memulai babak baru dalam hidupnya sebagai perkenier. Segala tata cara pengelolaan perkebunan pala dipelajari secara autodidak. Lambat laun, ia semakin andal, hingga dikenal sebagai The Last Perkenier atau Perkenier Terakhir, julukan yang disematkan oleh Kantor Berita Antara.

Sembari menyimak penuturan Mas Pongky, tangan saya terus “menari” membuat coretan—sketsa—gerbang rumahnya. Tak banyak warna yang saya pulaskan, hanya hijau, hitam, abu-abu dan cokelat, untuk menggambarkan lumut di dinding gerbang yang tinggi besar dan kokoh, khas bangunan kuno peninggalan Belanda.
Gerbang tersebut dilengkapi gapura yang berhiaskan huruf G di sisi kiri dan W di sisi kanan. GW merupakan singkatan dari Groot Waling atau Waling Besar, nama area perkebunan milik van den Broeke. Di dekat gerbang tepi pantai inilah saya dan teman-teman menyimak kisah hidup Mas Pongky yang seru, sekaligus menyedihkan.
Bagian yang menyedihkan: ketika Mas Pongky menceritakan tentang konflik yang dipicu oleh isu agama di Maluku, pada 1999. Para pelaku kerusuhan tak hanya memporak-porandakan rumahnya, tetapi juga mencederai anggota keluarga: dua anaknya yang sempat kritis segera dibawa ke Jakarta, dan berhasil diselamatkan.
Kini, anak perempuan dari Mas Pongky berdomisili d Yogyakarta. Sedangkan anak lelaki menetap bersamanya di Banda Besar. Mas Pongky berharap, si anak lelaki mau melanjutkan warisan tugas sebagai perkenier. Terlebih pala memiliki banyak manfaat dan dapat diolah menjadi beberapa produk, di antaranya minyak dan sabun pala.
Tak terasa sore menjelang, saya dan rekan-rekan harus segera naik kapal, berlayar kembali ke Banda Neira, sebelum laut pasang. Saya pun membereskan peralatan gambar. Senang rasanya bisa bertemu Mas Pongky dan menyelesaikan dua sketsa: gerbang rumah serta tempat pengasapan pala warisan leluhurnya yang legend.

Suatu saat nanti, saya ingin datang lagi ke Banda, dan membuat lebih banyak sketsa, yang bukan sekadar coretan, melainkan catatan perjalanan, juga sejarah. Sketsa memang lebih sederhana dibandingkan foto yang lebih detail dan praktis. Namun sketsa punya romansa, dan itulah yang menjadikan kenangan terasa berbeda.
Penulis: Nugraha Pratama, penggiat sketsa asal Jakarta
Editor: Vega Probo