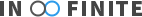Sebelumnya, di Bagian 1, telah diulas mengenai Prasasti Lonthoir, sumber primer, bukti jejak sejarah masa lampau mengenai eksploitasi rempah pala di Kepulauan Banda, Maluku Tengah, khususnya di Pulau Lonthoir. Juga, menjadi bukti penjajahan serta keserakahan kolonial Belanda terhadap inlander.
Di batu bersejarah itu terdapat tulisan dalam Bahasa Belanda yang terjemahannya berarti, “Pagar pembatas batu ini dibuat atas perintah Jan van den Broeke pada tahun 1706.” Diduga besar Jan adalah keturunan dari Pieter van den Broeke, pedagang yang bertugas di VOC, kongsi dagang Belanda.
Sedikit mengilas balik, pada 1599, Belanda pertama kali mencapai sepuluh pulau kecil di Banda yang pada saat itu merupakan satu-satunya daerah penghasil pala dan bunga pala. Mereka diterima dengan hormat oleh orang Banda yang berusaha menyingkirkan Portugis dan mencari sekutu yang kuat.
Semula, Belanda memang berniat untuk mengusir Portugis dari Negeri Rempah Banda. Lalu, sebuah kontrak pun dibuat antara Belanda dan penguasa Banda yang disebut dengan orangkaya. Namun keadaan menjadi berbalik ketika Belanda mulai membangun benteng dan pos perdagangan di Banda.

Belanda memiliki pemikiran khusus tentang perdagangan pala dan bunga pala. Tak tanggung-tanggung, mereka menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan tuntutan mereka. Belanda menginginkan orang Banda berkomitmen untuk berdagang rempah-rempah secara eksklusif dengan mereka.
Di sinilah, orang Banda baru menyadari keadaan mereka dengan masuknya bangsa Belanda ternyata lebih buruk dibandingkan sebelumnya—semasa kedatangan bangsa Portugis. Terlebih di daerah Lonthoir yang berada dalam pendudukan Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen.
Sebuah literatur (Loth, 1995, p. 5) menyebutkan, sejumlah orangkaya ditangkap dan diadili, dan 48 dari mereka dieksekusi dengan cara dipenggal. Keluarga orangkaya (sekitar 789 pria lansia, wanita, dan anak-anak) dikirim ke Batavia, beberapa dari mereka dipekerjakan sebagai budak dan dibuang ke Ceylon (sekarang Sri Lanka).
Invasi Belanda atas Banda makin menjadi-jadi. Mereka memporakporandakan desa-desa di wilayah pesisir. Orang-orang Lonthoir terpaksa lari dan menyelamatkan diri ke pegunungan. Namun setelah berbulan-bulan dikepung oleh Belanda, warga makin kesulitan untuk melawan balik.
Pada akhirnya, sekelompok besar pria, wanita, dan anak- anak lebih memilih kelaparan atau melompat dari tebing, daripada harus menyerah. Hanya sedikit yang berhasil membuat perahu dan melarikan diri pada malam hari ke Kepulauan Kei, Seram, Kisar, dan pulau kecil lain.
Data literatur (Loth, 1995, p. 6) menyebutkan, hanya sekitar 1.000 jiwa dari perkiraan 15.000 penduduk Kepulauan Banda yang tersisa. Sebagian tersebar di perkebunan pala sebagai pekerja paksa, karena Belanda memanfaatkan penduduk asli sebagai budak perkebunan.
Sebetulnya, Belanda lebih suka menggantikan penduduk asli dengan budak yang berasal dari luar negeri yang diperoleh dari pasar budak di pantai di wilayah dagang VOC. Sebab mereka menganggap orang Banda tidak dapat dipercaya dan umumnya enggan untuk berkontribusi pada produksi.

Selain itu, tidak banyak orang Banda yang tersisa. Sebagian mereka yang menjadi budak sudah melarikan diri, terutama selama tahun-tahun pertama. Meskipun pelarian biasanya hanya dalam kelompok kecil, tetapi karena frekuensi yang cukup sering maka menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda.
Dalam pelariannya, ada di antara para budak yang terjangkit penyakit dan mati. Mereka melarikan diri dengan bantuan budak lain yang sebelumnya melarikan diri ke Pulau Seram dan pulau-pulau sekitar. Hal ini membuat Belanda rutin berpatroli di laut sekitar Banda pada malam hari untuk mencegah para budak melarikan diri.
Belanda, yang semula “hanya” bermaksud melancarkan strategi monopoli (perdagangan pala), pada 1621, namun akhirnya benar-benar melumpuhkan Banda. Saat itu, Lonthoir merupakan satu-satunya wilayah yang berhasil menyelamatkan pohon pala walaupun sebagian besar desa dan bangunan hancur.
Banda luluh lantak dan pulau-pulaunya nyaris tak berpenghuni. Pasca pembunuhan massal terhadap 15.000 penduduk Banda, Jan Pieterszoon Coen meminta Heren XVII di Amsterdam agar perkebunan pala dikelola sebagai “petak bunga” oleh orang-orang dari Belanda, yang disebut perkenier.
Perkenier inilah yang mengelola bedeng pala, memelihara budak, dan memasok pala (dipanen dua kali setahun) kepada VOC. Tukang kebun menerima bagian dalam jumlah tetap dari VOC, begitu pula budak menerima gaji satu gulden per bulan, sejumlah beras dan garam, serta pakaian baru setahun sekali.
Jadi awal mula perkenier adalah warga sipil Belanda yang bersedia bermukim di Banda secara permanen dan memproduksi rempah-rempah bagi VOC. Mereka diberi hibah tanah di Banda dan bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik dan menyerahkan hasil panen dengan harga yang ditetapkan VOC.
Data literatur (Alwi, 2005, p. 127) menyebutkan, lahan-lahan produktif dibagi atas 68 persil atau disebut “perken” (perkebunan) berukuran sekitar 625 roeden persegi atau 12 sampai 30 hektare per perk. Seluruhnya ada 34 di Lonthoir, 31 di Pulau Ai, dan 3 di Pulau Neira serta diberikan hak kelola kepada 34–68 perkenier.
Dalam Plakaatboek 1602–1811, regulasi yang dikeluarkan pada 18 Februari 1721, tercatat bahwa menurut Raad van Justisie di Banda tidak ada warga sipil (lokal) yang dapat menjadi perkenier, melainkan khusus pegawai VOC. Adapun budak-budak diperas tenaganya untuk pekerjaan sulit: merawat perkebunan pala di pulau dengan kontur tanah berbukit- bukit.
Selama masa jabatan Gubernur Reinier de Klerk di Banda (1748–1753) perk-perk berkembang menjadi lebih produktif karena administrasi yang rapi dan teratur. Dalam Memorandum de Klerk tercatat bahwa pembelian pala dan fuli dengan harga 2 2/3 dan 18 stuiver tiap kilogram dan dijual kembali dengan harga 150 dan 256 stuiver.
Artinya, sebagaimana disebutkan literatur (Alwi, 2005, pp. 156-157), VOC memperoleh keuntungan 1.400 sampai 6.000 persen, Heren XVII menjual pala dan fuli dengan harga yang sangat tinggi. Satu pon fuli dibeli pada tahun 1750 dengan harga 45 sen, kemudian dijual kembali di pasaran Eropa sebesar 6,40 gulden.

Sayangnya, keuntungan besar itu tidak bertahan lama. Kebangkrutan terjadi pada 1778 karena terjadi letusan gunung api yang mengakibatkan kerusakan besar perk- perk, desa-desa, dan benteng di Neira.
Panen pala yang pada tahun 1777, menurut literatur (Alwi, 2005, p. 157), mencapai 400.000 kg pala dan 100.000 kg fuli, kemudian merosot drastis hingga 15.000 kg pala dan 5.000 kg fuli.
Situasi tetap sama hingga masa pergantian ke Nederlandsche Handels Maatschappij, penerus VOC yang bangkrut pada tahun 1799. Baru pada tahun 1864 terjadi perubahan pada saat penghapusan perbudakan dan diperkenalkannya perdagangan bebas. Pegawai kontrak menggantikan budak-budak pekerja.
Pemeliharaan pala dilakukan sesuai dengan cara yang diwariskan turun-temurun, salah satunya, yaitu jarak tanam antarpohon lima meter hingga enam meter. Sistem seperti itu sudah tidak digunakan oleh petani lain karena keterbatasan lahan. Sistem “perken” ini dimulai pada tahun 1626.
Dinasti Van Den Broeke
Seluruh Banda dibagi menjadi 68 perk. Perk pertama di Pulau Ai disewakan kepada Paulus van den Broeke. Ia menjadi perkenier terbesar di Kepulauan Banda pada paruh ke-dua abad ke-17. Van den Broeke memulai keuntungan pada tahun 1628. Sekitar tahun 1690, perk miliknya menghasilkan 10 ton pala dan tiga ton fuli.
Di Pulau Lonthoir, Paulus van den Broeke mewariskan perk kepada putranya, Jan Johannes van den Broeke, tepatnya di daerah Groot Walingen atau Walang Besar. Jan van den Broeke lahir dan meninggal di Banda Neira. Literatur (Indische Genealogische Vereniging, 2019) menyebutkan, ia menikah dengan perempuan Asia.
Nyaris tidak ada yang diketahui tentang dirinya. Satu bukti bahwa Jan van den Broeke memang berasal dari daerah Lonthoir adalah tulisan di Prasasti Lonthoir yang kini menjadi koleksi Museum Nasional. Namanya disebut dalam prasasti tersebut.

Dalam Regeringsalmanak tahun 1906 disebutkan bahwa W.F. van den Broeke memiliki perken yang berada di Distrik Lonthoir yang dikelola di bawah administrateur J.A. Delmaar. Pajak yang dibebankan adalah sebesar f995,70.
Pada tahun 1930-an, hanya satu perkenier yang tinggal dan bekerja di Kepulauan Banda, yaitu W.H.S van den Broeke, keturunan ke-sembilan dari Pieter van den Broeke (yang menetap di sana pada tahun 1614 sebagai salah satu perkenier pertama) dan cicit dari Paulus van den Broeke.
Pada masa pendudukan Jepang, tahun 1942, menurut literatur (Fries, 1991, p. 27),semua perkenier termasuk van den Broeke ditahan di Makassar. Baru setelah era Kemerdekaan, mereka kembali ke Banda. Tetapi seluruh areal perkebunan sudah diambil alih pemerintah Indonesia dan keluarga van den Broeke pun hidup dalam kemiskinan.
Wim van den Broeke, generasi ke-sepuluh, menjadi perkenier terakhir sampai tahun 1958 ketika semua perkebunan dinasionalisasi. Akhirnya, pemerintah mengembalikan sebagian perkebunan di Walang Besar kepada keluarga Van den Broeke seluas 12,5 hektare setelah, pada tahun 1976, ia dan ayahnya, W.H.S. van den Broeke, berjuang meminta haknya kembali kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Sejak Februari 1999, tanah di Walang Besar diambil alih oleh putranya, yaitu Paulus “Pongky” van den Broeke. Kini, ia menjadi perkenier terakhir di Banda dan hanya memiliki satu perkebunan seluas 12,5 hektare di Pulau Lonthoir.
Prasasti Lonthoir dan kisah perkenier ini menggambarkan betapa penguasaan sebuah wilayah oleh bangsa asing dapat terjadi karena adanya suatu power yang mampu melancarkan pengaruh untuk memaksakan kehendaknya.

Kini, Banda telah damai. Mini archipelago yang sebagian berwajah mini Europe ini menggambarkan sejatinya ranah yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja, yang memiliki kekayaan alam berlimpah, aman dan tenteram.
Penulis: Rully Handiani, sejarawan Museum Nasional Indonesia
Editor: Vega Probo