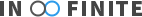Ada yang berbeda dari tari cakalele di tempat tinggalku, Desa Kampung Baru, dibandingkan di desa lain di Kecamatan Banda, Maluku Tengah. Memang, sama-sama menggunakan pedang, tombak, dan salawaku (tameng). Tetapi tari cakalele khas kampungku diawali dengan ritual adat buka puang atau buka kampong.
“Tari cakalele sudah ada sejak zaman dahulu bahkan jauh sebelum datangnya bangsa Belanda ke Banda Neira,” kata Mohtar Thalib, tokoh atau sesepuh adat Kampung Baru yang oleh warga biasa disapa dengan panggilan akrab Bapak Mo. Dari antua (beliau) lah diperoleh penuturan yang detail tentang tari cakalele.
Sebagaimana terlihat dari gerakan yang khas, ini adalah tari perang demi mempertahankan harga diri yang melambangkan jiwa kesatria yang bercirikan Islam. Biasanya, tarian ini ditampilkan di acara-acara tertentu. Nah, proses buka puang berlangsung pada malam hari, berlokasi di rumah adat Desa Kampung Baru.
Bisa dipastikan, pada malam itu suasana di sekitar rumah adat yang berdekatan dengan rumah nenekku pun meramai. Tampak beberapa pria—yang sudah menikah—bersiap untuk prosesi buka puang. Mereka berbusana rapi: memakai songko (kopiah atau peci), baju tokoa (koko), dan celana panjang.
Sebelum prosesi buka puang dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemukulan tiwal (tifa) oleh saudaraku yang biasa disapa Pak Malik. Seiring dengan itu juga disampaikan pesan dan kisah tentang penyelenggaraan buka puang pada masa kolonial Belanda. Ketika itu, pihak penjajah tidak mengizinkan ada keramaian atau kegiatan ibadah.
Tak kehilangan akal, warga Desa Kampung Baru pun berinisiatif “membungkus” kegiatan pengajian dalam kegiatan tradisional buka puang. Mereka menggunakan properti, salah satunya tempat siri, yang sarat nuansa lokalitas untuk menyimbolkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dengan cara ini, mereka mengelabui pihak Belanda.
Tempat siri yaitu wadah yang terbuat dari anyaman daun kelapa berbentuk bundar seperti mangkuk berisi beberapa helai daun sirih, kapur sirih, gambir, tembakau dan aneka bunga. Usai dilaksanakan kegiatan putar tempat siri, pada keesokan pagi, bapak-bapak membawa tempat siri sembari menapak tilas perjalanan orang-orang terdahulu.
Tempat siri dibawa ke area-area yang yang dinilai sakral dan berkaitan dengan suatu peristiwa di masa lampau. Lalu, sesampainya di Gunung Papan Berek, tempat siri diletakkan, dan prosesi dilanjutkan dengan sesi latihan tari cakalele. Tidak banyak warga yang bisa menyaksikannya, cuma mereka yang beroleh izin saja.
Tari cakalele dibawakan oleh lima orang yang memakai kostum seperti bangsa Portugis, masing-masing membawa tameng namun dengan senjata yang berbeda. Sebagian yang berperan sebagai kapitang membawa pedang dan tombak, sedangkan yang menjadi ulu balang memegang pedang dan salawaku.

Tari cakalele khas Banda memiliki tujuh gerakan inti. Namun tidak semua penari bisa melakukan ketujuhnya, paling-paling hanya tiga gerakan yang dibawakan secara berulang, plus “improvisasi” dengan gerakan tambahan. Tiap gerakan memiliki makna dan falsafah masing-masing.
Pertama, gerakan penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada tetua adat atau orang yang paling dituakan di Kampung Baru. Salah seorang penari melangkah ke depan dengan posisi berjongkok dan menunduk. Alat perang berupa pedang dan salawaku diletakkan di atas paha, sedangkan tombak disandarkan di paha.
Ke-dua, gerakan penghormatan penjemputan mama lima. Kali ini, penghormatan kepada para ibu yang diwakili oleh lima mama, masing-masing berbusana kebaya dengan tata rias rambut dikonde. Gerakan ke-dua kurang lebih sama dengan gerakan pertama, namun bukan hanya satu penari yang berjongkok, melainkan kelimanya.
Ke-tiga, gerakan penghormatan kepada para tamu, termasuk wisatawan dari dalam dan luar negeri. Gerakan ini biasanya ditampilkan di acara yang digelar di situs bersejarah, antara lain Istana Mini. Kelima penari memegang alat perang yang diletakkan di bagian bawah lutut kaki dengan posisi kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan.
Ke-empat, gerakan penghormatan kepada bendera. Secara bergantian, lima penari mengelilingi lima tombak yang masing-masing dipasang bendera (kain patola) dan dipancang di tanah. Menurut penuturan Bapak Mo, ini adalah gerakan penghormatan kepada kepala orang kaya Banda yang yang dibunuh oleh pihak Belanda (VOC).
Dahulu kala, Bapak Mo menambahkan, kepala orang kaya Banda—berjumlah 44 orang atau mungkin lebih—ditancapkan di ujung tombak, lalu dibawa keliling oleh pihak Belanda di depan keluarga korban. Menyimak penuturan Bapak Mo, air mata pun mengalir. Tak terbayangkan, betapa keji peristiwa pembantaian yang juga menimpa leluhurku.
Berikutnya, ke-lima, gerakan persiapan berperang. Secara bergantian, para penari bergerak sambil memegang alat perang—tombak—di tangan kanan, sebagai simbol kesiapan warga Banda berperang melawan kaum penjajah. Setelah ini, disambung dua gerakan inti yang menggambarkan pembelaan diri.
Gerakan para penari seperti menangkis, dengan kaki kiri maju selangkah. Menyaksikan gerakan pembelaan diri ini terbayang: dahulu kala, betapa gigih nenek moyang warga Banda mengusir kaum kolonial Belanda. Tentu saja dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk dapat menyerang dan melumpuhkan musuh.
Sungguh genius cara leluhur mengemas semangat patriotik dalam setiap gerakan tari cakalele yang dinamis, sehingga siapa pun yang menyaksikannya akan merasakan semangat yang sama. Di sisi lain juga sarat falsafah: betapa pentingnya memberikan penghormatan bagi tetua, ibu, tamu, dan membela negeri sendiri.
Menurut Dr. Jeanne Francoise dosen Universitas Pertahanan, tarian Cakalele ini termasuk Defense Heritage atau Warisan Pertahanan yang dimiliki Indonesia.
“Defense Heritage itu adalah segala objek cagar budaya, bangunan bersejarah, rumah, jembatan, kawasan, wilayah yang memiliki narasi sejarah perjuangan atau pertahanan bagi bangsa yang bersangkutan,” terangnya.
Seharusnya diteliti lebih lanjut, dibuat kajian dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda yang dimilik bangsa Indonesia.
Banda memang kaya!
Penulis: Fadhila Djauhari, guru honorer MAN 4 Maluku Tengah
Editor: Vega Probo